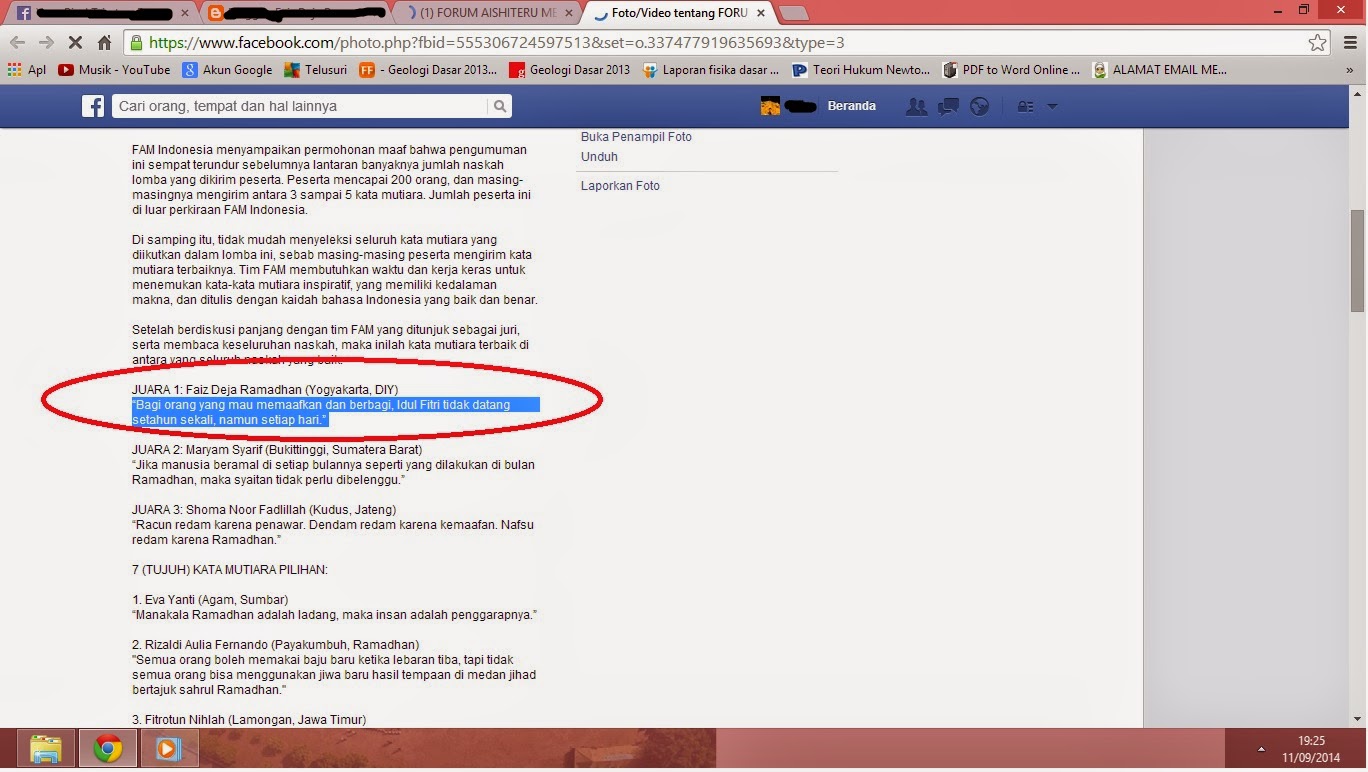Karya 23 :
“Sebuah Cerita” sebagai Juara 3 Lomba Cerpen
Nasional Xpressi Jurnal dan Politeknik Negeri Jakarta
SEBUAH
CERITA
tentang
aku, kampungku, dan masa lalu
Karya : Faiz Deja Ramadhan
Siang
di awal kelas,
Entah
hanya perasaanku atau memang cuaca terasa gerah. Pendingin ruangan sudah
maksimal pada angka 16
derajat sedari tadi, tapi aku masih saja mengipas-ngipaskan buku tulisku untuk
menghentikan keringat yang mencucur perlahan.
Jam masih saja lama menuju angka dua tanda bel pulang sekolah.
Satu-persatu teman aku amati nampak serius mendengarkan presentasi yang sedang
berlangsung di depan kelas. Baru sampai nomor urut ke enam, namun aku
semakin gugup saja. Menengok ke arah Dilan, dengan santainya dia mendengarkan
sambil sesekali membuka lembaran
kertas
pegangannya. Lita, gadis pintar itu nampak antusias mendengarkan, nampaknya dia
sudah siap dengan flash disk di
tangannya. Aku? Masih saja kebingungan, tulisan yang aku buat saja belum
sepenuhnya hafal. Sedangkan isi power
pointku juga hanya foto-foto pendukung ceritaku saja.
Pelajaran Bahasa
Indonesia
di jam terakhir yang membuat perutku mual tak karuan. Aku malu akan ceritaku
yang mungkin cuma
sederhana. Dino mempresentasikan suasana liburan saat di Singapura dengan keluarganya. Rio, dengan
bangganya memamerkan foto-foto saat dia berkunjung ke Raja Ampat. Begitu pula dengan Deni,
Fatmi, dan Cahyo. Apalah arti liburan yang aku tulis ini? Terkadang sekolah di tempat elit
membuat kebanggan tersendiri. Dianggap pintar atau beruntung oleh kebanyakan
orang, namun tekanan batin selalu aku rasakan, ya seperti saat-saat seperti ini contohnya. Aku
punya banyak teman di sekolah ini, tapi aku juga punya banyak malu di sini.
Minder lebih tepatnya. Setelah ini giliran Ajeng, lalu aku harus menyampaikan
cerita masa liburanku. Pasti ini tidak menarik sama sekali.
Sempurna,
sekarang giliranku menyampaikan apa yang sudah aku alami dengan gambar-gambar yang mungkin akan
membosankan bagi mereka. Aku mengawali ceritaku dari perjalanan kakiku yang
terasa berat meninggalkan bangku menuju depan kelas. Wajahku mungkin jadi pucat, keringat
masih saja membasahi.
“
Rian sudah siap?”
“
Sudah kok Bu.”
“
Kamu nampak pucat?”
“
Ah tidak apa-apa, sedikit kurang yakin aja dengan cerita Rian, Bu.”
“
Cobalah sampaikan!”
Memulai
percakapan dengan guru mata pelajaran setidaknya melatih agar lidah tak kaku
saat aku mulai bercerita tadi. Ini liburanku, ini ceritaku, dan inilah aku.
Memandang seisi kelas yang nampak masih antusias mendengarkan kisah liburan di
tempat-tempat menarik. Aku menganggap semuanya patung. Aku hanya berbicara
sendiri di ruang kelasku.
Di
awal presentasi aku putar sebuah video gabungan dari
hasil jepretanku, aku
pampang gambar kerbau yang gemuk, ayam-ayam, sungai bahkan persawahan yang
masih hijau. Ya sedikit membuat mereka keheranan, apa yang bakal aku sampaikan. Tetapi inilah cerita yang aku sampaikan.
Hai,
aku ingin bercerita tentang hariku dalam dua minggu kemarin. Aku tak
seberuntung kalian yang dapat menginjakkan kaki ke pulau-pulau indah di luar
sana, atau berbelanja dan menikmati wisata di negara asing. Bagiku itu hanya
mitos. Aku ingin bercerita tentang alam yang indah, alam yang penuh kenangan
turut serta membesarkanku dan memberiku pelajaran akan rasa syukurku. Aku
pernah mengalami semua itu. Aku tak pernah kemana-kemana, namun aku baru
menyadari jika kampung halamanku adalah sejarah hidupku yang mungkin
mengalahkan keelokan tempat-tempatyang kalian kunjungi. Aku juga terlalu sibuk
seperti kalian, belajar,
mengerjakan laporan, atau praktikum dan kegiatan ekskul lainnya, sehingga membuat aku
melupakan lingkungan kampung halamanku. Aku baru menyadarinya kemarin saat Bu
Ane menugaskan kita untuk membuat cerita singkat tentang liburan kita.
Kampungku,
aku awali dengan perjalananku di pematang yang luas. Aku masih dapat melihat
areal persawahan yang hijau dengan selang-seling warna muda dan tua, dengan
jalur-jalur jalan setapak
yang terbuat dari tanah. Aku bahkan dapat menangis merasakan ini. terakhir aku
menginjakkan kaki di persawahan adalah saat masih duduk di bangku kelas enam
sekolah dasar. Aku termenung
menatap gardu kecil yang bentuknya masih sama, dengan parit kecil yang ternyata
masih ada ikan kecil dengan ekor warna-warninya. Dulu aku dan teman-teman
sebayaku menangkap ikan-ikan
itu dengan anyaman bambu, orang Jawa
bilang itu besek. Tempat nasi yang biasa dipake kalau lagi ada hajat. Lalu kami
menaruhnya dalam ember kecil sebelum nanti dipindah ke dalam ember tanah liat,
atau sering di sebut maron. Bukan Maroon
Five.
Kami tidak cukup uang untuk membeli ikan hias atau aquarium saat itu, namun
kebersamaan itu terasa sangat mengharukan. Alam masih menjaga ikan kecil ini
hingga aku masih bisa melihatnya kemarin saat harus membuat tulisan ini. hanya
saja tak lagi ada kebun tebu di samping parit kecil. Aku tak bisa mengambil
batang tebu dan mengunyahnya hingga sari pati gula itu habis aku hisap. Aku membayangkan kenangan itu
dalam gardu kecil penuh kenangan. Suasana persawahan yang sepoi di kampungku. Memandang dengan lega
hamparan kesejukan. Di balik hijaunya masih saja ada gerumbul tanaman yang
tinggi, ditengah petak persawahan itu pohon kedondong menjulang tinggi.
Biasanya kami juga mencuri kedondong di tempat itu. Pohonnya pun masih ada saat
ini. perasaan membawaku terbang beberapa tahun yang lalu, sekarang tak ku lihat
anak-anak kecil mondar-mandir di sawah. Mungkin orang tua melarang mereka dan
menyuruhnya untuk belajar atau membiarkan anak-anak mereka sibuk dengan dunia
maya. Aku juga tak sempat melihat upacara Gagakan, upacara petani jawa yang
mempersembahkan makanan kepada Dewi Sri, pertanda terima kasih telah memberikan
tanaman yang subur. Maklumlah sekarang belum saatnya panen. Berjalan di tengah
pematang sawah membuat batin ini merasa lebih tenang meski panas terik menyorot
kulit. Setidaknya aku belajar mengingat masa lalu, belajar bersyukur memiliki
kenangan yang indah. Belum tentu remaja seusiaku dapat tinggal di kampung
sepertiku dengan sejuta kenangan tentang persawahan.
Sedikit
menghela nafas, jeda sejenak untuk menampilkan gambar kedua sebelum melanjutkan
ceritaku. Seisi kelas nampaknya masih memperhatikan ceritaku.
“
Apa kalian bosan dengan ceritaku?”
“
Sama sekali tidak Rian, aku justru suka. Aku belum pernah merasakan persawahan
secara nyata. Aku bahkan tidak pernah pergi ke kampung. Apakah kampung
halamanmu nyaman?”
“
Nyaman, kalau kita dapat merasakan yang seharusnya.”
Nah,
yang berikutnya ini adalah sungai yang biasa kami gunakan untuk bermain air.
Mungkin kalian sedikit berpikir bahwa kami ini jorok. Tapi cerita yang
seharusnya tidak seperti itu, dulunya sungai dalam foto itu berair sedang.
Tidak jernih, tidak juga sekeruh itu. Alirannya lumayan deras. Tak ada sampah
seperti yang di gambar. Kami banyak menghabiskan waktu di tempat itu, bermain
kapal yang kami susun dari batang-batang pohon pisang. Atau memancing ikan dari
atas jembatan gantung yang sekarang sudah tidak ada lagi. Katanya kena banjir
sekitar tujuh tahun yang lalu. Banjir bandang yang lumayan besar hingga meluap
hingga masjid dan sekolah di kampungku. Sejak saat ini sungai mulai berubah
fungsi yang bentuknya seperti dalam gambar. Banjir membawa air luapan dari kota
yang tak tertampung dan sampah yang hanyut di sungai, buangan dari orang-orang
kota pula. Sungai jadi lebih kotor, orang kampungku malah jadi ikut-ikutan membuang sampah
ke sungai pula karena melihat sungai mereka sudah kotor.
“
Kok sungai membawa sampah dan luapan air dari kota Rian?”
“
Ya, secara geografis kampung halamanku terletak di bagian selatan provinsi ini.
secara tidak langsung hujan yang mengguyur terus-menerus di puncak akan turun
ke kota dan membawa sampah-sampah yang menumpuk di sungai-sumgai dalam kota
kemudian berakhir di sungai daerah selatan, termasuk sungai yang mengalir di
kampung halamanku.”
Petani
di kampungku sangat tertolong dengan adanya sungai ini untuk pengairan, namun
tidak untuk anak-anak kecil saat ini.sungainya sudah tak sehat. Beda jauh
dengan jamanku dulu. Ternyata perubahan jaman membawa pengaruh yang sangat
besar. Tapi aku tak sekecewa itu. Aku masih dapat menyaksikan deretan pohon
kepuh atau dalam bahasa ilmiahnya sterculia
foetida yang masih berdiri sampai sekarang. Tidak begitu besar tapi jumlahnya
masih sama seperti saat aku tanam dengan kakakku waktu itu. Mungkin dia kurang
berkembang karena terhalang tanaman bambu atau yang lainnya. Setidaknya masih
bisa bertahan sampai saat ini. semoga bisa sebagai penyangga daerah aliran
sungai sehingga kampungku tak terancam bahaya erosi.
“
Inilah pohon yang aku maksud.”
Pohon
itu dari biji yang masih kecil. Biji yang berkembang menjadi tanaman kecil di
plastik putih yang aku
korek dari tempat sampah jaman dulu. Plastik baru masih susah didapat, tak
seperti sekarang ini. sungai sudah sedikit rusak bahkan tercemar, namun sungai
mengingatkanku akan masa kecilku di kampung halaman yang penuh keceriaan.
Belajar berenang
di sungai, bermain kapal dengan batang pohon pisang, dan berkemah di samping
sungai dengan api unggun kecil dan ubi bakar yang di dapat dari ladang.
Sekarang aku hanya bisa tersenyum geli mengingatnya, bahkan aku terbahak-bahak
di pinggir sungai saat mengambil gambar yang sekarang kalian lihat. Di sanalah aku dipukuli sama orang
tuaku karena mandi di sungai sampai lupa pergi pramuka. Sedikit bangga juga,
aku, kakaku dan teman-temanku sedikit berjasa melestarikan alam meski hanya
menanam lima pohon saja. Suatu awal mungkin, yang harus dipikirkan sekarang
adalah bagaimana menyadarkan masyarakat kampung agar tidak membuang sampah ke
sungai. Agar kampung halamanku menjadi bersih lagi, dengan sanitasi yang bersih
pula.
“
Aku sadar ceritaku tak seindah Raja Ampat atau cerita kalian dari luar negeri,
namun aku bangga memiliki kampung yang dapat aku bagi dengan kalian.”
Itu
tadi adalah dua tempat yang tak bisa dipisahkan dari kampung halamanku. Ada
sungai yang membelah kampungku menjadi dua dan persawahan yang masih menghijau
dan sesekali terlihat burung kuntul atau bangau sawah yang mencari katak.
Burung-burung pemakan padi juga masih banyak berterbangan disana, atau saat
musim kepompong tiba. Kepompong akan menetas dan ratusan kupu-kupu menghiasi
langit kampungku.
“
Lalu ada apa lagi?” Sahut
Fatma yang duduk di pojok kelas.
Banyak,
kalian dapat melihat dari urutan gambar di layar presentasiku.halaman yang tak
luas itu sering digunakan untuk berlatih tarian tradisional, yaitu Kuda Kepang, Jathilan masyarakat kami
menyebutnya. Dulu halaman itu luas. Aku sering menghabiskan
waktu di tempat itu pula, sekedar bermain kelereng, lompat tali, congklak, dan
permainan kampung lainnya. Bahkan saat purnama datang kami masih saja
menghabiskan waktu di halaman, menikmati rembulan, bermain petak umpet,
jejamuran dan sebagainya. Masa kecil kami begitu riang dengan nyanyian
anak-anak, celoteh dan tawa riang, bahkan cerita horor yang sering kami bagi di saat malam purnama
sampai kencing di celana karena menahan takut dari cerita itu. Sekarang aku tak
melihatnya lagi, halaman yang sudah semakin sempit dan anak-anak lebih memilih
bermain dengan televisi atau permainan yang lebih modern. Mungkin sekarang
bukan jamannya permainan tradisional lagi. Bahkan aku hanya bisa melihatnya di
museum dan angan-anganku saja tentang masa laluku di kampung tercintaku.
Mungkin
kalian masih bingung dan membayangkan bagaimana wujud kampungku. Sebenarnya
sering kampungku muncul di berbagai serial televisi. Meski hanya sebagai latar
persawahan atau rumah-rumahnya yang masih tradisional, namun sekarang sudah
banyak rumah yang di bongkar dan menjadi lebih modern. Budaya kota sudah mulai
merasuki. Kalau
kalian mau melihat, bisa datang ke kampung wisata di dekat kampung halamanku.
Kalian bisa bermain di sawah, memanen padi, membajak sawah
dengan kerbau, atau memainkan permainan
tradisional yang pernah aku mainkan dulu. Sambil belajar kalian dapat
menghargai alam dan budaya yang mulai ditinggalkan. Aku berharap semoga kisahku
tak akan hilang, semoga masih ada alam yang indah dan udara segar di kampung
halamanku dan kampung-kampung yang lainnya, bahkan kampung kalian semua yang
tak pernah ada sawah atau kerbau
atau yang ada juga gedung.
Entah
apa yang aku rasakan,
pengulangan sejarah tentang masa
yang telah lalu,
meski sekarang sudah sedikit
berubah, namun kampung halamanku,
memberi warna dalam hidupku, saksi
pembelajaran tentang hidup,
aku masih dapat merasakan indahnya
kampungku, aku beruntung,
dari mereka yang tak pernah melihat
sawah,
dari mereka yang tak merasakan air
sungai,
dari mereka yang bermain di
petak-petak sempit gang perumahan,
mungkin kampung halamanku akan
segera memudar,
tapi tak sepudar semangatku untuk
membanggakan kampungku yang telah berjasa,
untukku.
Tepuk
tangan riuh terdengar begitu semarak di dalam kelas, Bu Ane maju dan
merangkulku. Teman-teman tersenyun tanda puas mendengar ceritaku.
“Aku ingin cerita yang lebih panjang
sebenarnya Rian, tapi nanti yang lain tidak dapat kesempatan untuk menceritakan
liburannya.” Seru Bu Ane.
“Ah
ibu
bisa
saja, Rian hanya cerita seadanya saja, yang Rian sendiri tak pernah menyadari
kalau lingkungan tempat tinggal Rian begitu berubah. Rian tak pernah
memperhatikan Bu.”
“Ya,
dan kita bisa belajar dari Rian
untuk tetap mencintai kampung halaman kita apapun keadaanya dan dimanapun
kampung halaman itu berada, entah di pedesaan atau di kota. Iya kan Rian?”
Aku
hanya tersenyum menyambut kesimpulan dari Bu Ane, aku melangkah kembali ke
bangku dengan bangga, ternyata kampung halaman yang begitu kecil dengan kondisi
seadanya dapat menarik perhatian seperti halnya cerita teman-temanku yang lain
saat mereka menghabiskan banyak uang untuk membuat cerita mereka menjadi ‘wah’. Terimakasih kampung halamanku,
terimakasih kawan, dan terima kasih masa laluku. (FDR)